Bali kembali dilanda banjir. Kali ini, bukan lagi bencana alam biasa, namun balasan dari alam yang dilukai, ruang hijau yang digusur menjadi hotel, vila, beach club, hingga kolam renang privat. Pembangunan pariwisata terlalu rakus?
Banjir itu merendam Bali pada 10 September 2025 setelah hujan ekstrem mengguyur Pulau Dewata selama 24 beruntun. Bali pun lumpuh.
Curah hujan pada 9-10 September itu memang cukup tinggi. Dilaporkan curah hujan pada hari itu di atas 150 mm, bahkan tercatat mencapai 385 mm yang setara dengan curah hujan dua bulan di Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aktivitas warga di enam kabupaten/kota di Bali lumpuh. Wisatawan terjebak di hotel. Akses ke banyak destinasi turis putus. Restoran dan kafe terendam.
Banjir itu menelan nyawa 18 orang, juga berdampak kepada ratusan orang. Sangat mengerikan saat bukan lagi nama yang disebut, melainkan statistik.
Yang menyakitkan tidak ada permintaan maaf dari pemerintah juga dari dewan usai banjir besar di Pulau Dewata itu. Bahkan, orang nomor satu Bali Gubernur Wayan Koster sempat menolak banjir diakibatkan alih fungsi lahan.
 Gubernur Bali Wayan Koster. (Rizki Setyo/detikBali) Gubernur Bali Wayan Koster. (Rizki Setyo/detikBali) |
Pada 12 September, Koster menyampaikan pendapat bahwa alih fungsi lahan lebih banyak terjadi di wilayah Badung dan Gianyar, bukan di Denpasar, kawasan yang terdampak banjir paling parah.
"Nggak juga, alih fungsi lahan kan di Badung, Gianyar. Di Badung (alih fungsi lahan) di daerah-daerah Kuta Utara. Ini (Denpasar) kan jauh," kata Koster saat ditemui di lokasi pembongkaran ruko terdampak banjir di Jalan Sulawesi, Denpasar, dilansir detikbali, Jumat (12/9).
Padahal, obral izin pembangunan di Bali sudah berulang kali diberitakan. Perubahan hutan dan sawah menjadi bangunan beton berkali-kali diungkapkan. Sungai dan sempadan disulap jadi lahan komersial bukan sekali dua kali diprotes.
 Warga negara asing (WNA) membersihkan lumpur dan sampah akibat bencana banjir di kawasan Sungai Badung, Denpasar, Bali, Minggu (14/9/2025). (Nyoman Hendra Wibowo/Antara) Warga negara asing (WNA) membersihkan lumpur dan sampah akibat bencana banjir di kawasan Sungai Badung, Denpasar, Bali, Minggu (14/9/2025). (Nyoman Hendra Wibowo/Antara) |
Mestinya mudah mendeteksi lahan-lahan yang berubah fungsi itu di Bali. Tidak mungkin Pemprov Bali tdiak memiliki peta daerah dan rencana tata kota. Selain itu, Bali secara tradisional dibangun merujuk kepada Tri Hita Karana. Situs resmi Dinas Kebudayaan Buleleng secara lugas menyebutkan bahwa Tri Hita Karana adalah filosofi dan kearifan lokal masyarakat Bali yang diyakini sebagai kuncii kesejahteraan warga Bali.
Dan kunci itu digunakan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam tiga aspek utama kehidupan, yaitu hubungan dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan dengan sesama manusia (Pawongan), dan hubungan dengan alam semesta (Palemahan).
Konsep itu menjadi landasan spiritual dan etika bagi masyarakat Bali dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta menjadi panduan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan lestari.
Ya, Bali sudah mengenal keberlanjutan jauh sebelum muncul secara formal dan teridentifikasi sebagai istilah resmi pada 11 November 1966 melalui Konferensi Daerah Badan Perjuangan Umat Hindu Bali.
Garis waktu itu lebih dulu ketimbang definisi pembangunan berkelanjutan yang diusung dalam Brutland Report 1987. Forum itu merumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan generasi mendatang.
Tri Hita Karana juga diundangkan lebih dulu daripada Konferensi Stockholm yang merupakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diadakan di Stockholm, Swedia, pada 1972, dan menjadi konferensi global pertama yang mengangkat isu lingkungan hidup secara internasional.
Konsep Tri Hita Karana itu bahkan sudah diyakini sebagai sebuah filosofi hidup dan kearifan lokal yang berbasis Hindu dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali jauh sebelum itu. Tri Hita Karana adalah warisan dari para leluhurnya.
 Warga berjalan melewati lumpur pasca terjadi banjir di Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). (Nyoman Hendra Wibowo/Antara) Warga berjalan melewati lumpur pasca terjadi banjir di Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). (Nyoman Hendra Wibowo/Antara) |
Sayangnya, sebagian pihak justru mengabaikannya. Bisa jadi tahu ada Tri Hita Karana itu tapi tidak mau tahu. Salah satu yang jelas mengabaikan dan tidak mau tahu itu adalah si pemberi izin pendirian bangunan beton yang mengakibatkan ketidakseimbangan manusia dengan alam.
Dan, saat keseimbangan itu diabaikan, saat alam diremehkan menjadi sekadar alat untuk mencari cuan, air pun tak segan menenggelamkan.
Dan, semua itu disuguhkan pada 10-11 September. Air hujan yang begitu deras gagal meresap ke dalam tanah. Air itu mengalir terus tak tertampung. Air itu semakin deras dan membawa apa saja, laptop berisi skripsi, motor, mobil, bahkan rumah, dan anggota keluarga.
Pakar lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menyebut bahwa banjir itu menjadi alarm serius mengenai kerentanan ekologi dan tata ruang Bali.
"Banjir Bali 2025 bukanlah kejadian alamiah semata, melainkan akumulasi krisis tata kelola lingkungan dan ruang yang mendesak untuk ditangani secara strategis," kata Mahawan.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa kawasan resapan air di Bali menyusut drastis selama 20 tahun terakhir, meningkatkan risiko banjir dan longsor saat hujan deras melanda.
Walhi lebih dulu mengungkapkan antara 2018 hingga 2023, wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) kehilangan ribuan hektare lahan sawah akibat alih fungsi untuk pembangunan, dengan penyusutan tertinggi terjadi di Tabanan sebesar 2.676 hektare.
Walhi juga menyatakan perkembangan wilayah yang tak terkendali itu mempersempit ruang resapan air dan membuat Bali kian rentan terhadap banjir serta dampak perubahan iklim.
Ya, banjir di Bali bukan hanya soal saluran air tersumbat atau musim hujan yang ekstrim, melainkan cerminan dari kegagalan mengatasi akar masalah perubahan iklim dan model pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Secara jelas bahwa ada hubungan sebab akibat antara saat ruang hijau dipersempit maka alam kehilangan kemampuannya untuk menahan air, menyerap panas, dan menstabilkan iklim lokal.
Dan, perlu diketahui bahwa saat ini menurut laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2023, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dengan risiko meningkatnya kejadian banjir dan bencana alam lainnya jika pembangunan tidak mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Sayangnya, respons Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat mengunjungi korban banjir di Bali pada 13 September terlalu normatif. Terlalu biasa buat Bali yang menjadi destinasi wisata global dengan keunggulan sebagai wisata hijau dan spiritual.
 Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana seusai meninjau Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali pada Sabtu (13/9/2025). (Karsiani Putri/detikBali) Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana seusai meninjau Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali pada Sabtu (13/9/2025). (Karsiani Putri/detikBali) |
Pernyataan yang dimunculkan menpar hanya sebatas imbauan agar wisatawan tetap merasa aman dan yakin kegiatan pariwisata tidak terganggu oleh banjir.
Menpar sama sekali tidak menaruh fokus kepada evaluasi tata ruang atau strategi mitigasi bencana, melainkan pada citra Bali sebagai destinasi wisata. Yang bisa jadi dimaknai oleh banyak pihak sebagai persetujuan untuk melanjutkan pola konsumsi yang merusak lingkungan. Langkah apapun boleh yang penting pariwisata Bali pulih.
Menpar tidak menyatakan betapa model pembangunan pariwisata di Bali sudah begitu rakus mencaplok ruang dan tanah milik warga lokal dan bagaimana proyek-proyek besar merampas ruang hijau dan mengorbankan tata kelola lingkungan.
Yang semua itu mengabaikan Tri Hita Karana, melupakan keseimbangan.
Menpar juga tidak menyinggung soal perubahan iklim, krisis iklim, yang bisa berdampak lebih mengerikan buat pariwisata Bali. Banjir besar bisa saja terulang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan sudah memprediksi bencana itu datang lagi.
Begini kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada 16 September: "Tujuannya pariwisata di Bali harus pulih, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa bencana tidak berhenti di satu kejadian. Ia akan berulang, apalagi jika faktor pemicunya tetap ada."
Bukan itu saja, jika kerusakan lingkungan di Bali terus diabaikan, seperti banjir yang kian sering terjadi, bukan tidak mungkin konsekuensinya meluas hingga level internasional sebagaimana yang terjadi pada Great Barrier Reef di Australia. Kerusakan Great Barrier Reef yang diakibatkan suhu air laut meningkat itu tak lagi hanya jadi persoalan lokal, tapi sorotan global. Tekanan buat pemerintah Australia untuk menanganinya pun otomatis meluas.
Menpar, Koster, dan semua pihak tidak boleh menutup mata. Andai perusakan lingkungan di Bali terus berlanjut, bisa saja muncul tekanan internasional terhadap Bali.
Testimoni dari turis asing, juga stempel dari badan internasional laiknya UNESCO tidak bisa diabaikan, sebab bagaimana pun penilaian itu menjadi acuan wisatawan dunia dalam memilih destinasi liburan. Citra negara juga bisa memburuk karena pemerintah dinilai gagal dalam memenuhi komitmen lingkungan internasional.
Jika citra Bali hijau dan spiritual tercoreng, konsekuensinya tak hanya reputasi, tapi juga ekonomi dan sosial. Ekonomi pemerintah, juga ekonomi warga, dan pekerja wisata, serta usaha terkait. Begitu pula dengan kehidupan sosial warga.
Wisata Bali dibangun bukan dalam satu malam, namun sudah sejak zaman kolonial. Nah, apa iya apa yang sudah dibangun secara turun-menurun itu bikin kita rela jika hancur begitu saja?
Apa iya pembangunan pariwisata dengan cara menambah bangunan beton dan menghapus hutan dan sawah adalah jalan utama menuju kemajuan ekonomi Pulau Dewata?
Apakah Bali akan tetap mampu menjadi magnet wisatawan andai tidak ada lagi sawah dan subak, air jernih di sungai-sungainya, laut biru dan pasir putih di pantai-pantainya, juga tanpa keramahan warga yang terluka karena kehilangan tanah dan kendali atas ruang hidupnya?
Jadi, sudah saatnya banjir besar pada 10 September lalu menjadi refleksi.
Sebelum luka dan kerusakan Bali sorotan dunia, sebelum tekanan itu semakin besar, dan tentu saja agar warga Bali tidak menderita dihantam banjir lagi, sebelum sawah dan hutan betul-betul habis, berbagai upaya konkret untuk menyelamatkan Bali. Dan, langkah perbaikan itu bukan hanya pada teknis (infrastruktur), tapi juga kultural dan politis.
Bahwa mari mulai meyakini bahwa pembangunan hotel, vila, dan resort bukanlah semata-mata menjadi tanda kemajuan. Juga, sebaliknya bahwa mempertahankan sawah dan ruang hijau tidak sama dengan menghambat investasi. Sudah saatnya pemegang kebijakan dan warga Bali kepada Tri Hita Karana.













































 Upload Photo
Upload Photo
 Write a Story
Write a Story

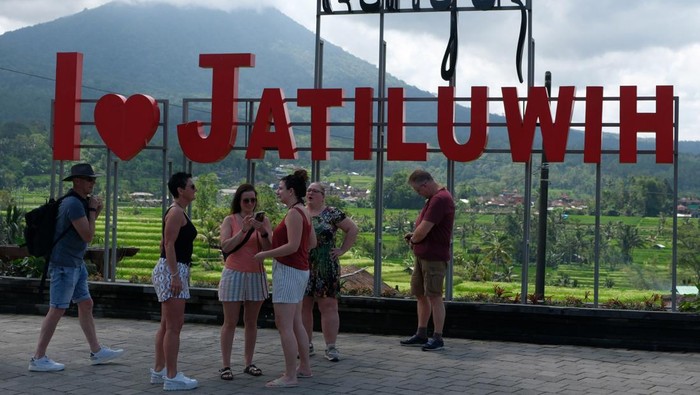








Komentar Terbanyak
Potret Sri Mulyani Healing di Kota Lama Usai Tak Jadi Menkeu
Keunikan Kontol Kejepit, Jajanan Unik di Pasar Kangen Jogja
Daftar Negara yang Menolak Israel, Tidak Mengakui Keberadaan dan Paspornya